
Lentera Atma: Kepala Penuh Judul
Aku selalu berpikir takut itu datang tiba-tiba, seperti kabar duka atau pesan singkat yang salah kirim. Tapi takut pada skripsi tidak begitu. Ia datang pelan, menetap, lalu hidup bersamaku tanpa pernah minta izin.
Awalnya sederhana. Sebuah pengumuman di grup kelas tentang pengajuan judul. Lalu obrolan santai di kantin yang tiba-tiba dipenuhi kalimat, “Kamu ambil dosen siapa?” dan “Data kamu sudah sampai mana?” Aku mengangguk, tersenyum, pura-pura santai. Padahal di kepalaku, kata skripsi bergema seperti palu yang terus memukul dari dalam.
Setiap kali membuka laptop, aku menatap layar kosong lebih lama daripada menulis satu kalimat. Kursor berkedip seperti mengejek, seolah berkata: ayo, mulai saja. Tapi memulai berarti mengakui bahwa aku benar-benar di sini, di tahap ini, tidak bisa lagi bersembunyi di balik tugas kelompok atau presentasi dadakan. Skripsi menuntut sesuatu yang lebih jujur: pikiranku sendiri, keberanianku sendiri.
Aku takut bukan karena tidak punya ide. Justru sebaliknya. Terlalu banyak ide membuatku lumpuh. Setiap judul terasa kurang layak, setiap rumusan masalah terdengar bodoh setelah kubaca ulang. Aku membayangkan dosen pembimbing mengernyit, membaca tulisanku dengan sabar yang dipaksakan, lalu berkata, “Coba dipikirkan lagi.” Kalimat itu terdengar sopan, tapi bagiku artinya jelas: kamu belum cukup.
Malam-malamku dipenuhi niat yang selalu ditunda. Aku berkata pada diri sendiri, “Nanti setelah makan,” lalu, “Nanti setelah satu episode lagi,” sampai akhirnya jam dua pagi dan aku memilih tidur dengan perasaan bersalah yang tidak sempat kuhabiskan. Besoknya, rasa bersalah itu berubah menjadi takut, lalu takut berubah menjadi diam. Lingkaran itu terus berulang, rapi dan kejam.
Yang paling menakutkan dari skripsi bukanlah halaman-halamannya, melainkan apa yang menunggunya di akhir. Setelah skripsi selesai, tidak ada lagi status “sedang berproses.” Tidak ada alasan untuk tidak tahu arah. Skripsi seperti garis tipis yang memisahkan aku hari ini dengan versi diriku yang dituntut lebih siap, lebih pasti, lebih dewasa. Dan jujur saja, aku belum yakin ingin menyeberang.
Kadang aku iri pada teman-teman yang terlihat lancar. Mereka bicara tentang bab tiga seperti membicarakan cuaca. Aku mendengarkan sambil bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tidak takut, atau hanya lebih pandai menyembunyikannya. Aku sendiri terlalu lelah untuk berpura-pura berani.
Namun di sela-sela ketakutan itu, ada momen kecil yang jarang kuakui. Saat satu paragraf akhirnya jadi. Saat satu referensi terasa pas. Saat aku membaca ulang tulisanku dan berpikir, oh, ternyata aku bisa sejauh ini. Momen-momen itu singkat, cepat hilang, tapi cukup untuk membuatku kembali membuka laptop keesokan harinya.
Aku belum berdamai dengan skripsi. Masih sering takut, masih sering menunda. Tapi sekarang aku tahu: rasa takut ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang penting. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan melihat halaman-halaman ini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saksi bahwa aku pernah ragu, pernah takut, dan tetap berjalan pelan, tapi tetap maju.
Image by BuonoDelTesoro from Pixabay








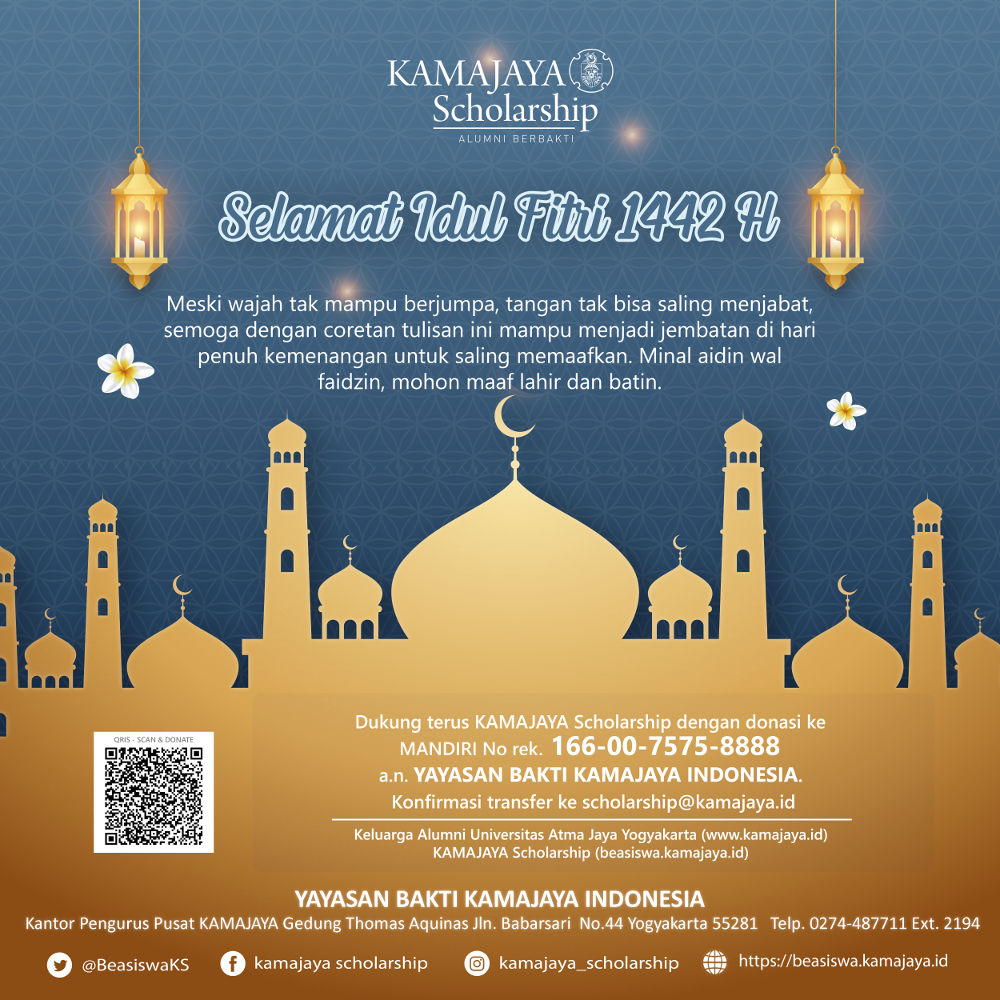




No Comments