
Coretan Mahasiswa: Ketika Pertemanan Kuliah Menjadi Racun Emosional
Ketika seseorang membayangkan masa kuliah, sering kali yang terlintas adalah kebebasan, eksplorasi diri, dan tentu saja, membangun jejaring pertemanan yang luas. Masa-masa menjadi mahasiswa dianggap sebagai “masa keemasan” untuk bertumbuh secara intelektual dan sosial. Namun, di balik narasi ideal itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan: perasaan kesepian yang lahir bukan dari ketiadaan teman, tetapi dari berada di lingkungan pertemanan yang tidak sehat—atau lebih tepatnya, toxic.
Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut menghadapi tekanan akademik, tugas yang menumpuk, atau dosen yang menantang, tetapi juga harus bergelut dengan realitas sosial yang rumit. Salah satunya adalah pertemanan yang tidak mendukung. Ironisnya, kita bisa berada dalam satu kelompok, bercanda dan tertawa bersama, tetapi merasa benar-benar sendirian di dalam hati. Kenapa? Karena hubungan tersebut dibangun bukan atas dasar dukungan dan empati, melainkan persaingan, manipulasi emosional, dan standar sosial yang menekan.
Yang paling menyakitkan adalah ketika kita merasa tidak bisa keluar dari lingkaran itu karena takut dianggap “berubah”, “sombong”, atau bahkan kehilangan satu-satunya teman yang ada. Pertemanan toxic bukan hanya soal drama sosial. Dalam jangka panjang, ia bisa berdampak pada kesehatan mental, bahkan performa akademik mahasiswa. Rasa minder, overthinking, burnout sosial, dan hilangnya motivasi belajar sering kali bermula dari tekanan lingkungan yang tidak mendukung. Kita menjadi tidak percaya diri, terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, bahkan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan kuliah.
Beberapa mahasiswa memilih untuk diam dan menyimpan semuanya sendiri. Mereka takut dicap “berlebihan” atau “tidak kuat mental”. Padahal, mengakui rasa tidak nyaman adalah langkah awal dari penyembuhan. Kampus seharusnya menjadi tempat yang inklusif, bukan arena kompetisi sosial yang membungkam perasaan. Dalam situasi seperti ini, menjadi “sendiri” bukanlah kutukan. Justru, itu bisa menjadi momen untuk mengenali kembali siapa kita dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tidak semua orang yang tersenyum pada kita adalah teman. Tidak semua kelompok yang ramai berarti tempat yang tepat untuk tumbuh.
Mulailah dari menyaring interaksi. Bangun batasan sehat. Belajar mengatakan “tidak” pada hal-hal yang menyakiti mental. Dan yang paling penting, berani keluar dari lingkaran pertemanan yang membuat kita merasa kecil dan tidak cukup. Jangan takut dicap “drama” atau “sensitif”, karena menjaga kesehatan mental jauh lebih penting daripada mempertahankan relasi yang mematikan pertumbuhan.
Menjadi mahasiswa bukan berarti harus selalu kuat. Tidak semua pertemanan akan bertahan, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kita tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Jika hari ini kamu merasa sendiri karena memilih menjauh dari toxic circle, ingatlah: itu adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Kamu tidak sendiri—ada banyak mahasiswa lain yang sedang melalui hal yang sama, dan perlahan, sedang membangun kembali dirinya dengan penuh harapan.








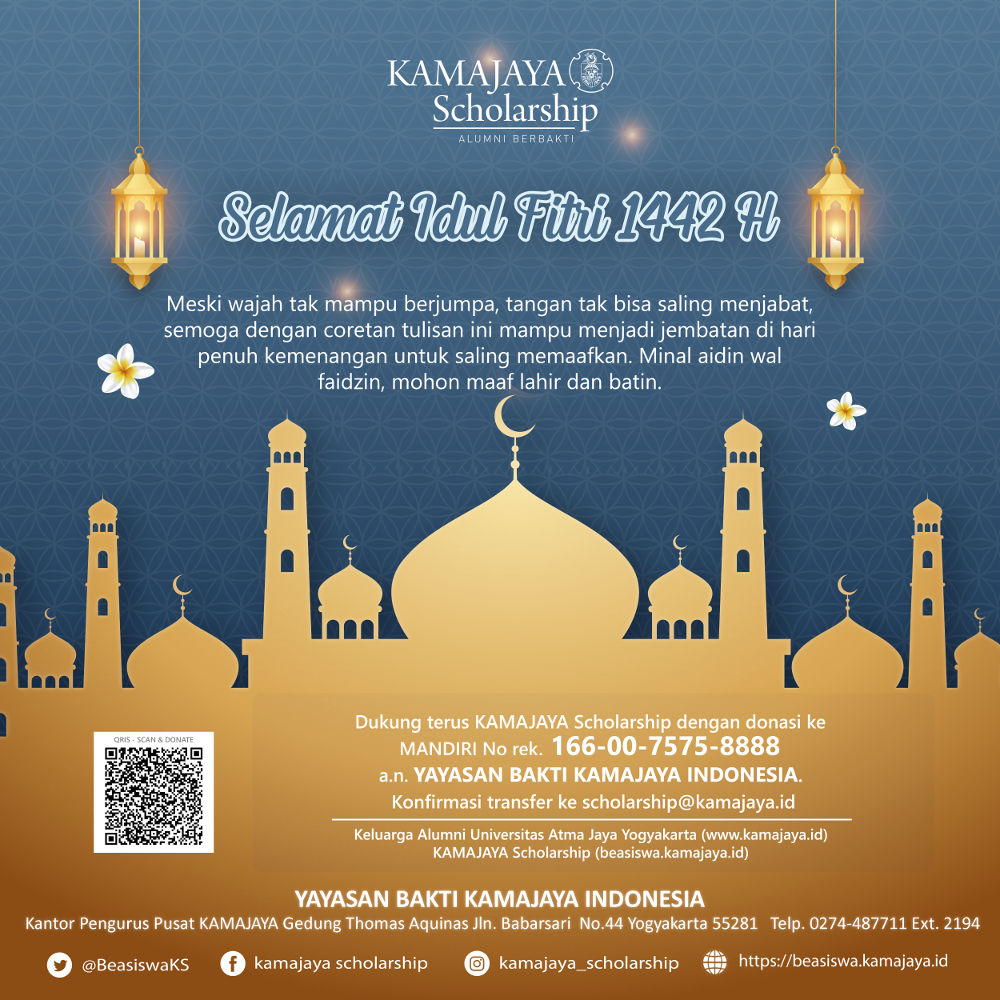




No Comments