
Opini: Self-Diagnosis dan Romantisasi Gangguan Mental: Antara Kesadaran dan Misinformasi

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental mulai mendapatkan perhatian lebih luas, termasuk di kalangan mahasiswa. Kampanye publik, konten media sosial, dan diskusi terbuka di berbagai platform mendorong banyak mahasiswa untuk lebih sadar akan kondisi psikologis mereka. Namun, di balik meningkatnya kesadaran tersebut, muncul fenomena baru yang perlu diwaspadai yaitu tren self-diagnosis dan romantisasi gangguan mental. Alih-alih membawa dampak positif, fenomena ini justru bisa menyesatkan dan menunda penanganan yang tepat.
Self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri tanpa keterlibatan profesional kesehatan mental kerap terjadi di lingkungan kampus. Mahasiswa yang merasa stres berat, mudah cemas, atau mengalami perubahan suasana hati ekstrem sering kali langsung menyimpulkan bahwa mereka mengalami gangguan seperti anxiety disorder, depresi, bahkan ADHD, hanya berdasarkan hasil kuis daring, konten di media sosial, atau pengalaman orang lain yang dibagikan secara publik. Hal ini tentu berbahaya karena diagnosis gangguan mental bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan proses evaluasi yang kompleks dan menyeluruh oleh psikolog atau psikiater yang kompeten.
Selain itu, fenomena romantisasi gangguan mental turut memperkeruh keadaan. Di media sosial, gangguan seperti depresi dan anxiety sering digambarkan secara estetis dan puitis, seolah-olah itu adalah bagian dari identitas keren atau keunikan diri. Unggahan dengan estetika murung, caption mendalam, atau kutipan dari tokoh terkenal kadang membuat gangguan mental terlihat “menarik” dan “relatable”. Ini bukan hanya mereduksi penderitaan nyata yang dialami oleh orang dengan gangguan mental, tapi juga membuka celah bagi individu untuk mengklaim identitas gangguan tersebut tanpa dasar kuat. Tren ini bisa berdampak serius, terutama bagi mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan pertolongan profesional. Karena merasa sudah memahami dirinya sendiri, mereka cenderung enggan berkonsultasi dengan tenaga ahli. Tak jarang, mereka mencoba mengobati diri sendiri dengan cara yang salah, seperti mengonsumsi obat penenang tanpa resep, menarik diri dari lingkungan sosial, atau bahkan memvalidasi kondisi mereka dengan konten yang justru memperburuk keadaan. Ini dapat memperparah kondisi psikologis dan menghambat pemulihan jangka panjang.
Penting untuk diingat bahwa meningkatnya kesadaran tentang kesehatan mental memang langkah awal yang baik, tetapi harus disertai dengan literasi yang benar. Mahasiswa perlu memahami bahwa gangguan mental bukan tren atau label untuk memperkuat identitas. Mengalami stres, sedih, atau cemas adalah hal yang wajar dalam kehidupan, tetapi tidak serta-merta menandakan adanya gangguan klinis. Justru, mengenali kapan harus meminta bantuan profesional adalah bentuk keberanian dan kedewasaan.
Oleh karena itu, institusi pendidikan, organisasi mahasiswa, dan komunitas kampus perlu aktif memberikan edukasi kesehatan mental berbasis sains dan empati. Media sosial juga harus menjadi ruang yang bertanggung jawab, bukan hanya tempat berbagi, tetapi juga sumber informasi yang valid. Di tengah era digital yang serba cepat, mahasiswa perlu dibekali kemampuan memilah mana yang merupakan kesadaran kritis, dan mana yang hanya misinformasi yang bisa membahayakan diri.
“Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, tapi bukti keberanian untuk mencintai diri sendiri.”
Yogyakarta, 10 Juli 2025
Diah Ariyanti
Mahasiswa Program Studi Biologi UAJY Angkatan 2023
Penerima Beasiswa KAMAJAYA Angkatan ke-8








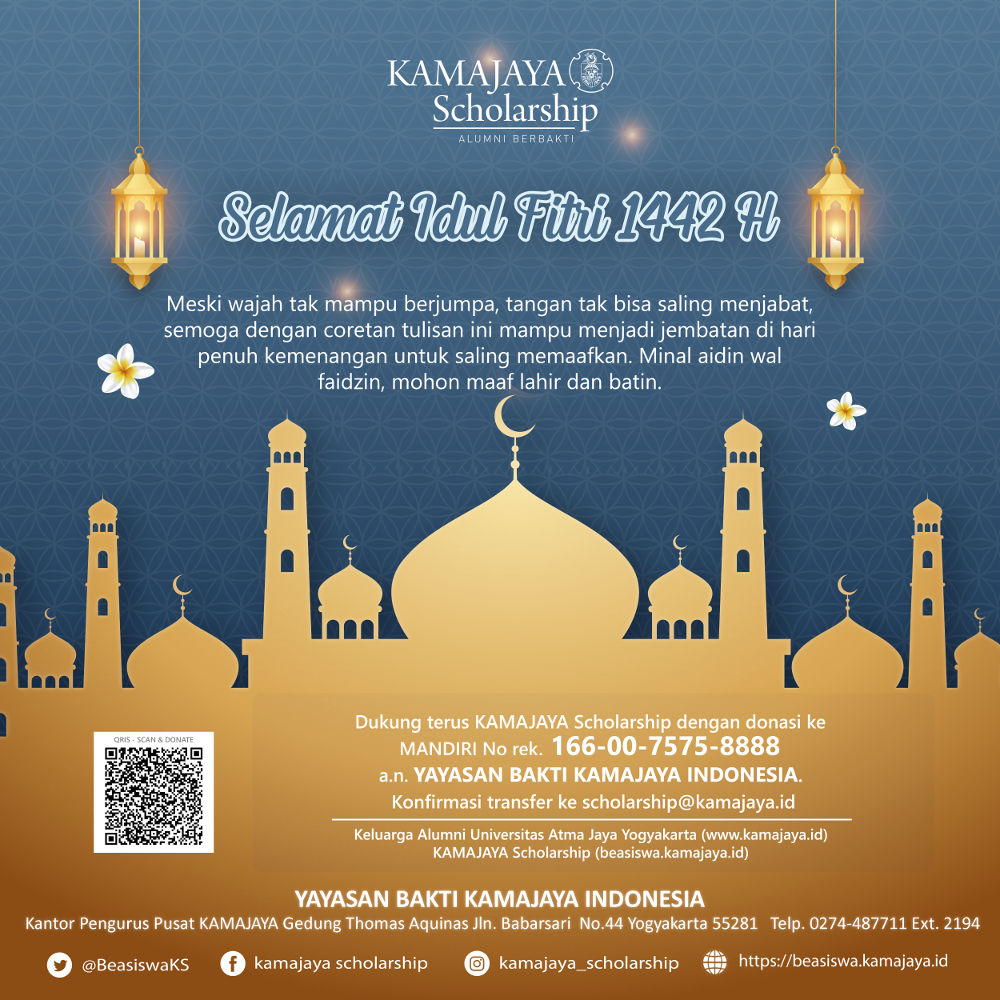




No Comments